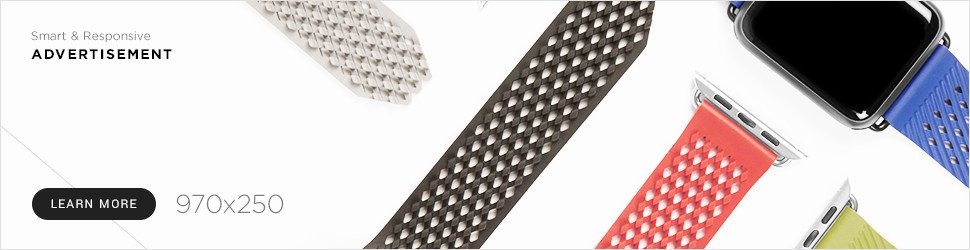EKO Prasetyo dalam buku “Orang Miskin Dilarang Sekolah” (2004) menyebut bahwa sistem pendidikan di Indonesia bisa menjadi kapitalistik ketika tidak memberi ruang bagi kaum mustadl’afin untuk menjadi orang pintar.
Sinisme tersebut kini menemu sinar cerah, sebab pemerintah di tahun 2023 telah mengalokasikan 20% anggaran APBN sebesar 612,2 Triliun. Di saat yang sama, belum lama ini ini data angka putus sekolah tahun 2022/2023 kembali meningkat sejumlah 76.834 orang. Dari catatan Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat 76% keluarga mengakui penyebab utama anak mereka putus sekolah adalah karena ekonomi.
Sungguh ironis, dalam benak sebagian orang, dengan anggaran fantastis tersebut terbayang akan sesuatu yang serba gratis. Dalam pikiran siswa, mereka mungkin hanya dituntut untuk berangkat sekolah saja tanpa harus membebani orang tuanya dengan biaya apapun termasuk membayar SPP, buku-buku dan alat -alat pelajaran. Sebab ia berpikir semua telah disediakan dan diberikan sekolah secara gratis, sehingga tidak ada lagi kasus bunuh diri karena tidak mampu membayar sekolah.
Demikian juga dengan para guru, mereka tidak perlu memikirkan kekurangan gaji yang biasanya mereka rasakan setiap selesai gaji bulanan, begitu pula dengan para karyawan, mereka tidak merasa risau hanya gara-gara masalah uang. Ini memang tidak sekadar bayangan dan angan masyarakat, pemerintah telah menggelontorkan anggaran pendidikan 2022/2023 tersebut antara lain melalui kebijakan program Indonesia pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Sungguh, kebijakan itu cukup melegakan terutama bagi orang-orang lemah, kaum miskin dan orang kecil lainnya, paling tidak untuk masa sembilan tahun pendidikan anak-anaknya (kebijakan ini berlaku untuk tingkat PAUD, SD dan SMP).
Ketika Presiden Jokowi mencanangkan pendidikan gratis melalui program-program tersebut, berbagai elemen masyarakat menyambut dengan antusias. Banyak yang gembira, tetapi tidak sedikit yang pesimis.
Tujuan utama kebijakan sekolah gratis itu sendiri (pemerintah memberi istilah Bantuan Operasional sekolah) adalah guna meningkatkan akses masyarakat untuk memperoleh pendidikan dasar, mengurangi tingkat putus sekolah di tingkat pendidikan dasar yang masih tinggi, serta menghapuskan peristiwa–peristiwa yang memalukan dalam pendidikan, seperti kasus siswa bunuh diri karena tidak mampu membayar biaya sekolah.
Sepintas, kebijakan ini kembali mengangkat popularitas pemerintah, dan melupakan kita pada proses latar belakang lahirnya kebijakan itu. Kita memang sudah terbiasa dilupakan dengan sistem gali lubang tutup lubang yang sering dilakukan pemerintah dan biasanya hanya menguntungkan sekelompok orang saja.
Meminjam analisa Milan Kundera, bahwa kita sering lupa terhadap kesalahan politik, dan (pe)lupa(an) tersebut tentu di ciptakan oleh penguasa. Hanya saja untuk kebijakan sekolah gratis ini minimal kita bisa berharap akan merasakan secara langsung manfaat dari sesuatu yang semestinya menjadi hak kita.
Ketika presiden membuat keputusan berani itu sebagai i’tikad baik mengimplementasikan amanat konstitusi dan UU sistem pendidikan nasional, ternyata tidak diimbangi dengan kemampuan mengurai langkah strategis tadi secara baik dan cerdas dari para pembantunya; menteri-menteri terkait. Sehingga kebijakan hanya berkutat pada hal–hal teknis. Dalam hal ini, Kemendikbudristek dan Kemenag terkesan mendahulukan aspek–aspek teknis operasional pemberian bantuan itu dengan mengesampingkan substansi dari tujuan pokok yaitu pendidikan dasar gratis .
Dikutip dari kompas.com, pada kelanjutannya, aspek teknis itu menimbulkan masalah-masalah. Terbukti, dalam petunjuk pelaksanaan yang masih belum tersosialisasi dengan baik banyak mengandung petunjuk yang membingungkan dan tidak mempunyai dasar hukum kuat. Sehingga membuka kemungkinan terbukanya peluang bagi sekolah yang bersangkutan menarik iuran tambahan dengan dalih untuk meningkatkan mutu pendidikan, para penyelenggara pendidikan khususnya kelas menengah atas, mengganggap dana yang diberikan pemerintah belum cukup untuk meningkatkan kualitas pendidikan mereka.
Persoalan redaksional dari aturan teknisnya pun menimbulkan tafsiran lain dalam implementasinya. Kata `boleh` dalam juklak itu bisa di tafsirkan sebagai opsi bagi sekolah untuk menarik iuran tambahan. Padahal dalam praktiknya nanti -sesuai dengan perjanjian antara pihak sekolah dan pemerintah-, pihak sekolah dilarang membebani siswanya dengan iuran tambahan.
Hal ini membuat sekolah-sekolah tertentu merasa keberatan, semisal sebuah sekolah swasta di Jakarta yang secara tegas menolak bantuan operasional tersebut, karena adanya konsekuensi, tidak bisa meminta iuran tambahan dari siswa yang tidak sepadan dengan target pendidikan mereka. Mereka menganggap dengan hanya menggunakan bantuan itu, belum cukup untuk meningkatkan mutu pendidikan, membiayai guru dan karyawan.
Dikutip dari Kompas.com, lucunya menteri pendidikan nasional merespons hal keberatan sebagian sekolah dengan tidak mengharuskan sekolah swasta yang sudah mapan ikut kebijakan tersebut. Jelas kebijakan itu mengesankan keterpaksaan dan ketidakmerataan dari subsidi yang ada.
Di samping itu, persoalan teknis penyampaian bantuan juga menambah kesangsian sebagian pihak terhadap prospek kebijakan ini, karena berdasar pengalaman yang dahulu, banyak sumbangan dan bantuan dari pemerintah tidak sampai sebagaimana mestinya, serta belum adanya perangkat-perangkat hukum yang jelas. Ini sebagai cerminan kebijakan yang akan pemerintah terapkan masih setengah hati (half heartedly).
Kalau melihat lebih jauh sebenarnya persoalan pendidikan tidak hanya diselesaikan hanya dengan sekolah gratis, meskipun setidaknya kebijakan ini sebagai awal yang baik bagi dunia pendidikan kita yang sedang terpuruk. Minimal kita nanti bisa memperbaiki peringkat pendidikan dengan negara-negara Asia Tenggara, karena pada 2023 ini kita menduduki peringkat ke-4 setingkat di bawah Thailand.
Persoalan lain dunia pendidikan yang tidak kalah krusialnya adalah persoalan geografis. Banyak desa-desa di daerah, terutama sekali di daerah pedalaman dan tertinggal yang belum mempunyai sekolah sendiri. Sehingga siswa yang ingin bersekolah harus ke desa lain, sementara untuk sampai ke lokasi belajar, mereka harus menempuh jarak yang cukup jauh dan medan yang berat.
Fenomena itu mestinya menjadi perhatian pemerintah, dalam hal ini Kementrian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Sekolah-sekolah baru dan akses yang mudah mestinya menjadi prioritas, sebagai upaya mengejar ketertinggalan dari daerah lain.
Penting juga menjadi perhatian pemerintah adalah memperlakukan secara adil pada lembaga pendidikan non pemerintah semisal pesantren–pesantren. Diakui atau tidak, pesantren adalah sedikit dari sistem pembelajaran yang memiliki pola dan orientasi pendidikan yang kuat dan stabil serta dengan biaya terjangkau.
Pesantrenlah yang hingga sekarang tetap istiqomah dengan konsentrasi pendidikan keagamaan yang notabene menjadi benteng moral yang efektif bagi generasi selanjutnya. Tetapi selama ini pemerintah menganggapnya sebagai pendidikan alternatif sehingga perhatian yang pemerintah berikan tak lebih dari pemberian-pemberian yang relatif tidak sama dengan sekolah milik pemerintah.
Satu lagi persoalan pendidikan yang sering luput dari perhatian pemerintah adalah kendala yang masih dominan dirasakan masyarakat yaitu krisis ekonomi yang berkepanjangan. Masyarakat merasa selama ini kebijakan pemerintah sering tidak memihak kepada mereka. Implikasinya, mereka hanya di sibukkan pemenuhan sehari -hari; bagaimana memberi makan dan menghidupi keluarganya, sehingga persoalan pendidikan yang penting bagi anak–anaknya pun, jauh dari jangkauan mereka.
Akhirnya, guna menggerakkan kebijakan dan menjawab permasalahan pendidikan di atas, maka dibutuhkan peran serta masyarakat dan para wakil rakyat. Pelaksanaan dan pengawasan kebijakan yang telah atau akan di implementasikan pemerintah penting di sini, terutama kebijakan-kebijakan yang populis, seperti sekolah gratis tersebut, sehingga tercapai tujuan pendidikan yang di inginkan bersama dan menguntungkan bagi masyarakat banyak.
Wallahu a’lam